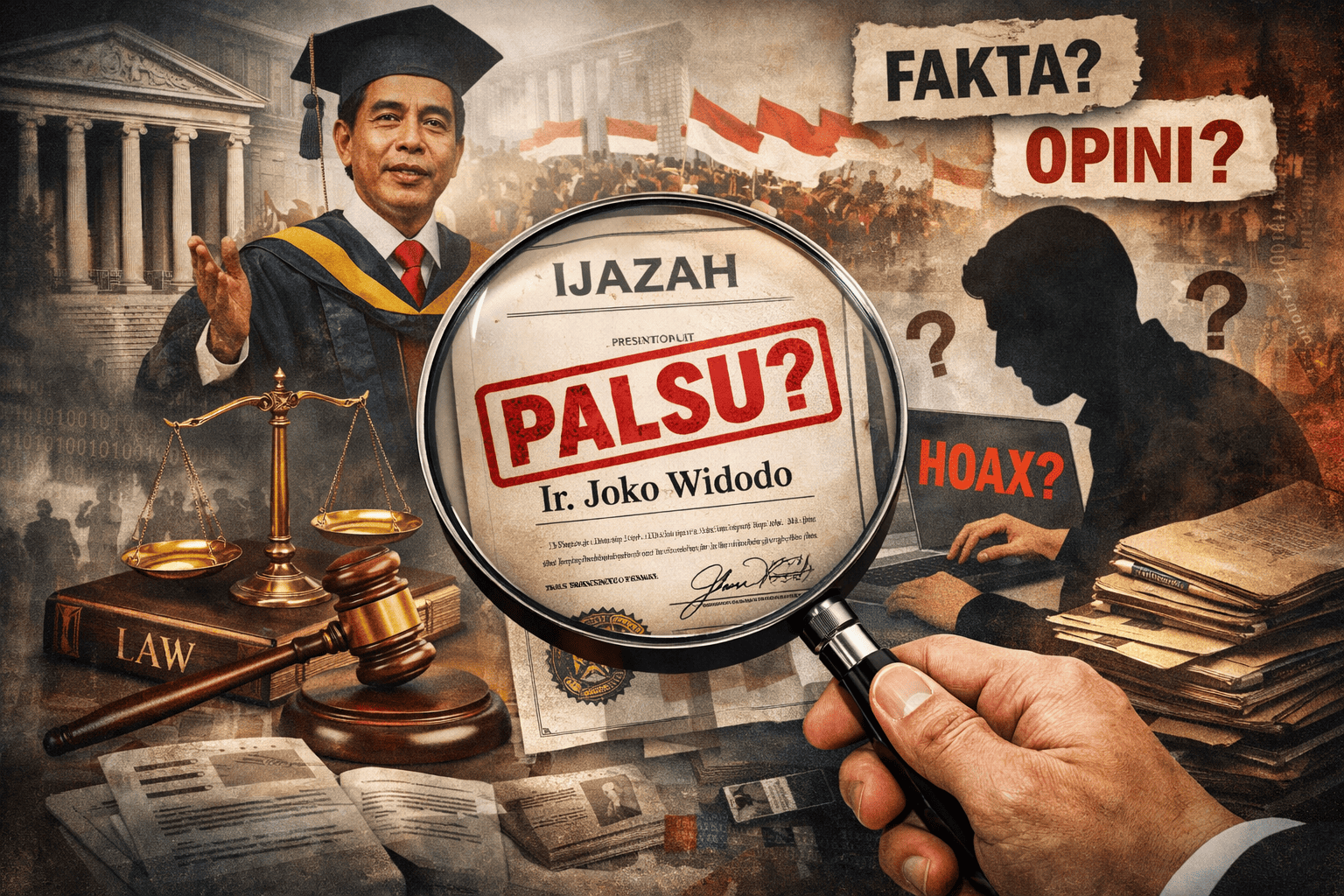Oleh: Surti
Wardani
Kita sedang
hidup dalam fase sejarah ketika kecepatan menjadi mata uang utama. Bukan hanya
dalam ekonomi dan teknologi, tetapi juga dalam cara manusia memahami, merasakan,
dan membentuk hubungan. Di ruang digital, yang memadatkan jarak, memendekkan
waktu, dan mempercepat aliran pesan, komunikasi mengalami pergeseran mendasar.
Kita tidak hanya berbicara lebih cepat, tetapi juga berpikir dan merespons
dalam ritme yang makin mendesak. Pertanyaannya: apa yang hilang ketika
komunikasi bergerak terlalu cepat?
Dari
perspektif kultural, era digital menciptakan budaya baru yang dapat disebut
sebagai budaya percepatan makna. Budaya yang memprioritaskan reaksi
cepat sebagai standar kecerdasan sosial: merespons segera berarti mengikuti
arus, memahami tren, dan tetap relevan. Namun budaya ini secara diam-diam
meluruhkan norma-norma komunikasi yang sebelumnya memberi ruang bagi
kontemplasi, keheningan, dan perenungan. Dalam banyak masyarakat, terutama di
Asia, percakapan mendalam dan jeda diam dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan.
Kini, nilai itu digantikan oleh kebutuhan untuk “selalu hadir” di platform
digital. Di sinilah terlihat benturan antara ritme kultural yang lambat dengan
ritme algoritmik yang cepat.
Secara
psikologis, percepatan komunikasi menciptakan beban kognitif baru. Komunikasi
digital menuntut kita untuk terus memproses informasi dalam jumlah besar dan
dalam kecepatan tinggi. Otak dipaksa mengelola pesan yang masuk tanpa henti, dari
notifikasi singkat hingga diskusi daring yang tidak pernah berakhir.
Konsekuensinya muncul dalam bentuk keletihan digital, ketidakmampuan
mempertahankan fokus, dan melemahnya sensitivitas terhadap pesan yang lebih
kompleks dan emosional. Kita terbiasa membaca cepat, bukan memahami; merespons
cepat, bukan memaknai.
Dalam
konteks teori komunikasi, fenomena ini dapat dibaca melalui Teori Media
Richness yang dikembangkan Daft dan Lengel. Menurut teori ini, efektivitas
komunikasi ditentukan oleh “kekayaan media” atau kemampuan media menyampaikan
nuansa dan konteks. Media digital yang cepat dan singkat, seperti pesan instan,
komentar, atau unggahan singkat, adalah media miskin yang tidak dirancang untuk
percakapan berlapis makna. Ketika masyarakat mulai mengandalkan media miskin
untuk isu-isu berat, yang terjadi adalah penyusutan kedalaman. Kita mencoba
memaksa kompleksitas ke dalam kalimat pendek, meme, dan emoji, seolah makna
dapat disederhanakan tanpa kehilangan esensinya.
Teori lainnya, Communication Accommodation Theory dari Howard Giles, menjelaskan bagaimana manusia cenderung menyesuaikan gaya komunikasinya dengan orang lain atau lingkungannya. Di ruang digital, penyesuaian ini tidak lagi terjadi pada individu, melainkan pada struktur algoritmik. Pengguna menyesuaikan tempo komunikasi mereka dengan logika platform, cepat, ringkas, dan reaktif, untuk tetap terlihat, terbaca, dan relevan. Kita bukan lagi menyesuaikan diri dengan manusia lain, tetapi dengan mekanisme digital yang menentukan visibilitas dan perhatian.
Data terbaru
memperkuat fenomena ini. Sebuah penelitian tahun 2024 yang melibatkan 4.200
responden di lima negara Asia Tenggara menemukan bahwa 68% pengguna media
sosial merasa “terdorong” untuk merespons pesan secepat mungkin karena takut
dianggap tidak peduli atau tidak update. Studi lain pada 2023 menunjukkan bahwa
pengguna yang terlalu sering terpapar komunikasi cepat mengalami penurunan
kemampuan membaca mendalam hingga 23%, terutama di kalangan usia 18–30 tahun.
Kedua temuan ini menegaskan bahwa kecepatan bukan hanya memengaruhi pola
interaksi, tetapi juga mengubah cara kerja kognitif dan emosional manusia.
Namun yang
paling penting adalah konsekuensi kemanusiaannya. Komunikasi mendalam
membutuhkan kualitas yang tidak bisa dipercepat: empati, perhatian, dan
kesediaan untuk mendengarkan. Ketika semuanya dipadatkan menjadi respons
instan, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar hadir bagi orang lain.
Relasi yang seharusnya dibangun dengan sabar menjadi tergantikan oleh hubungan
yang didasarkan pada ritme notifikasi. Kedalaman digantikan performa; makna
digantikan kecepatan.
Dalam
perspektif nilai kemanusiaan, kita perlu mengingat kembali bahwa komunikasi
bukan sekadar pertukaran informasi. Ia adalah proses membangun kepercayaan,
berbagi pengalaman, dan memahami sesama. Kemanusiaan tidak bergerak dalam
kecepatan kilat; ia berdenyut dalam ritme yang pelan, penuh perhatian, dan
penuh ruang untuk jeda.
Karena itu,
tantangan kita di era digital bukanlah memperlambat teknologi, itu mustahil, melainkan
memperlambat diri kita sendiri. Mengambil jeda sebelum merespons, membaca
hingga selesai sebelum beropini, bertanya sebelum menyimpulkan, dan hadir untuk
mendengarkan tanpa tergesa. Menciptakan kembali ruang kedalaman dalam dunia
yang mendesak kita untuk terus bergerak cepat adalah bentuk perlawanan kecil
yang sangat manusiawi.
Pada
akhirnya, kita tidak sedang berperang dengan teknologi, tetapi dengan
kecenderungan kita sendiri untuk menyerah pada ritme yang tidak sejalan dengan
kebutuhan kemanusiaan. Komunikasi yang cepat mungkin membuat kita lebih
terhubung, tetapi hanya komunikasi yang mendalam yang membuat kita lebih
memahami. Dalam pusaran notifikasi yang tidak pernah berhenti, memilih untuk
kembali pada kedalaman adalah langkah untuk menjaga diri tetap utuh sebagai
manusia.
Daftar
Pustaka
Daft,
R. L., & Lengel, R. H. Media
Richness Theory: Organizational Information Requirements, Media Capabilities,
and Structural Design.
Addison-Wesley, 1986.
Giles, H. Communication Accommodation Theory. In: Berger, C. R., Roloff, M. E., & Roskos-Ewoldsen, D. (Eds.). The Handbook of Communication Science. SAGE Publications, 2009.
Hadi,
M., & Rachman, A. (2024). “Digital Response Pressure and Perceived Social
Obligation Among Young Adults in Southeast Asia.” Journal of Digital Interaction Studies, 12(1), 45–63.
Santos, R., Nguyen, L.,
& Wirawan, D. (2023). “Reading Depth Decline in High-Frequency Social Media
Users: A Cross-Cultural Study.” New Media & Cognition
Review, 7(3), 112–130.